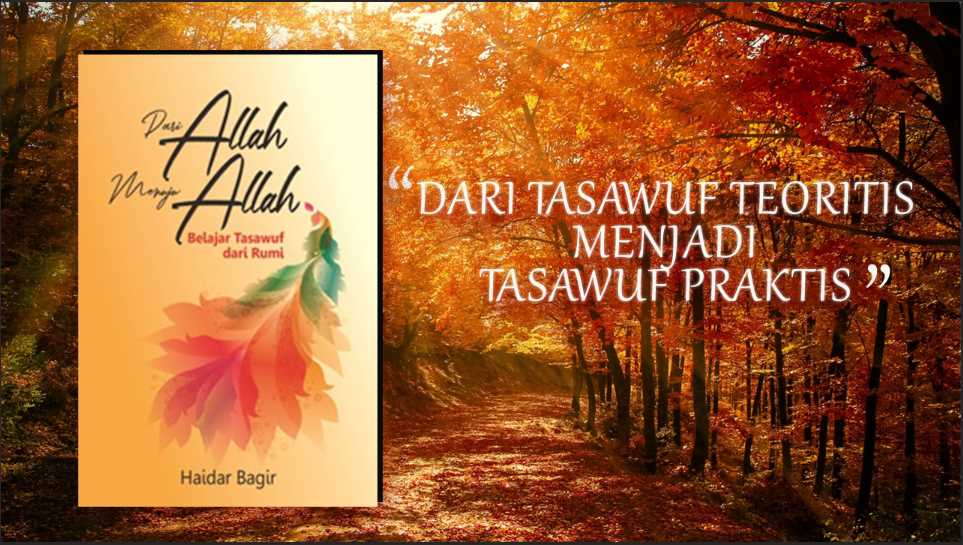Oleh: Dayu Aqraminas
Direktur Ma’had Tarbiyah al-Mujahadah
Sampai saat ini masih ada kelompok yang tidak setuju dengan mengkombinasikan syari’at dengan tasawwuf dalam praktik keislaman.Terutama Wahabi yang menolak cara berpikir sufi, karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran Sunnah. Tidak hanya Wahabi, sebagian kelompok formalistik atau legal formal-fiqh juga menolak tasawuf karena menganggap metodologi yang digunakan kaum sufi dalam menginterpretasikan nash tidak sejalur dengan mereka.
Metodologi yang dimaksud adalah metode dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, kelompok sufi tendensi menggunakan metode isyārī dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Menurut al-Zarqānī dalam Manāhil ‘Irfān, “Suatu metode yang mentakwilkan ayat-ayat tidak secara lahir (tekstualis). Namun menggunakan indikasi yang bersifat khaffi (rahasia), tentunya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang bertasawuf.” Padangan ini juga sejalan dengan Muhammad Husain al-Dzahabi, bahwa tafsir isyārī merupakan metodologi penafsiran yang bisa dilakukan oleh praktisi tasawuf.
Dari defenisi di atas, terlihat sekali bahwa metodologi yang digunakan oleh sufi hanya berputar kepada makna supra-rasional. Alasan inilah yang membuat mereka menganggap bahwa tradisi sufi tidak mampu berfikir rasional dalam memproduksi dan menginterpretasi makna Alquran. Selain itu, prinsip penafsiran yang digunakan oleh sufi kebanyakan bersumber dari pengalaman batin yang dikenal dengan ‘ilm mukasyafah.
Hemat saya, tuduhan-tudahan kelompok anti-sufi itu tidak dibenarkan, banyak sekali ulama yang berkomentar positif terkait sufi dan metodologinya, salah satunya Fakhruddīn al-Razī yang terkenal dengan magnum opus-nya berjudul Mafātih al-Ghaib. Menurutnya, “Ketahuilah! banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak mau menyebut diri mereka sufi, itu tidak dibenarkan. Karena ucapan sufi memberikan jalan untuk mengenal Allah dan mereka adalah sebaik-baiknya manusia”.Senada juga disampaikan oleh Imam al-Suyūṭī di dalam al-‘Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’an, menurutnya kita tidak boleh menegasikan makna batin ketimbang berputar-putar dengan makna lahir (tekstual) seperti yang dilakukan oleh kelompok formalistik. Hanya saja yang mampu melakukan penafsiran secara isyarī ituhanya orang-orang tertentu yakni mereka yang terpilih dan dibukakan pintu keilmuannya oleh Allah swt.
Begitupun dengan Ibn ‘Ajiba, yang memberikan concern lebih terhadap tasawuf bahkan mengharmonisasikan syariat dan tasawuf lewat karya-karyanya. Ia keturunan Hasanī yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Mahdi bin al-Husain bin Muhammad. Dikenal dengan panggilan Ibn ‘Ajibah yang diambil dari nama daerahnya A’jabisy Tetouan Maroko. Ibn ‘Ajibah lahir pada tahun 1161 H/1758 M, sekitaran tahun ini menunjukkan ia sezaman dengan Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari yang merupakan ulama besar kota Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan.
Ibn ‘Ajiba bisa dibilang multi-disipliner dalam keilmuan, terbukti ia menghasilkan karya-karya dari berbagai bidang keilmuan, bahkan setiap bidang menghasilkan lebih dari satu buku, di antarnya: bidang tafsir salah satunya Bahr al-Madīd fi Tafsīr Alquran al-Majīd, bidang hadis seperti al-Anwār al-Saniyyah fī al-Adzkār al-Nabawiyyah, bidang fikih Hāsyiah ‘ala Mukhtashar Khalil, bidang bahasa al-Futūhāt al-Qudūsiyyah fī Syarh al-Muqaddimah al-Jārumiyyah dan bidang tasawuf Mi’raj at-Tasyawwuq ila Haqaiq at-Tasawwuf.
Mengharmonisasikan Syari’ah dan Tasawwuf lewat Tafsir
Tidak banyak ditemukan ulama seperti Ibn ‘Ajibah yang mengharmonisasikan syariat dan tasawuf yang diakomodir dalam satu buku tafsir. Kebanyakan para ulama sufi hanya memberikan pengaruh dan doktrin sufi saja di dalam karya tafsirnya tapi tidak memberikan embel-embel fikih seperti Haqā’iq al-Tafsir karya al-Sulamī, Tafsir Alquran al-‘Adzīm karya al-Tustarī, dan Latā’if al-Isyārī karya al-Qusyairi. Begitu pun sebaliknya, hanya tendensi dengan kajian fikih saja seperti: Ahkām Alqur’an karya al-Jashshās, Ahkām Alqur’an karya Ibn al-‘Arabī, dan al-Jāmi’ li Ahkām Alqur’an karya al-Qurtubī.
Berbeda dengan Tafsir Ibn ‘Ajibah berjudul Bahr al-Madīd fi Tafsīr al-Qur’an al-Majīd (Lautan Panjang dalam Penjelasan Alquran yang Mulia), yang memberikan nuansa baru dalam kajian tafsir. Dalam tafsir Bahru al-Madid, cara kerja penafsiran Ibn ‘Ajibah tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya. Ia memberikan sumber-sumber Alquran, hadis, menjelaskan sisi bahasa, histori dan lainnya.
Selanjutnya ia memberikan pandangan-pandangan legal-formal (fikih), dan diakhiri dengan pembahasan sufistik yang ditandai dengan term al-Isyārah yaitu penafsiran-penafsiran yang dilakukan secara isyārī. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa Ibn ‘Ajibah terlebih dahulu menjelaskan legal-formal (fikih) daripada penafsiran isyārī? Bagi Ibn ‘Ajibah makna teks (dzhahir) harus didahulukan kemudian baru masuk ketahapan makna isyarī
Mungkin tujuannya agar pembaca dari kalangan awam bisa mengerti dan ada ekuilibrium (keseimbangan) antara pejelasan secara teks dan isyarī. Ibn ‘Ajibah ketika menafsirkan suatu ayat melakukan diversitas (pembeda) antara kajian fikih dan tasawuf, tentu ini sangat menguntungkan bagi orang awam, karena tidak semua orang awam bisa memahami maksud dari penafsiran isyārī.
Misalnya di dalam QS. al-Fātihah [1], pembahasan awal yang dilakukan oleh Ibn ‘Ajibah adalah pandangan fikih terkait dengan basmalah. Ia menjelaskan dari sudut mazhab fikih, status basmalah dalam Alquran karena kaitannya bisa mempengaruhi dalam shalat. Penjelasan selanjutnya sama seperti yang dilakukan oleh mufasir sebelumnya, yaitu menjelasakan sisi bahasa, asbāb al-nuzūl, qira’at dan lainnya. Dan penjelasan terakhir mengenai penafsiran-penafsiran ‘isyārī. Dalam penafsirannya juga ia mengutip mufasir sufi terdahulu, seperti Abū Hāmid al-Ghazali, Imam al-Qusyairī, al-Tustarī, dan lainnya.
Dari karya tafsir Ibn ‘Ajibah ini mengajarkan kita, bahwa ajaran syariat dan tasawuf tidak bisa dipertentangkan dan tidak mungkin ditinggalkan salah satunya. Karena dalam praktik keagamaan, syariah dan tasawuf harus diaktualkan.
Kalimat penutup dari penulis, mengutip pandangan Jalāl al-Bishri dalam al-Mausu’ah al-Yūsufiyyah fī Bayān Adillah al-Shufiyyah: “Tauhid mewajibkan seseorang beriman, orang yang tidak beriman tidak ada tauhid pada dirinya. Begitupun syariat mewajibkan seseorang untuk beradab apabila tidak ada adab, maka tidak ada syariat, iman, tauhid pada dirinya”.
Wallahu ‘Alam