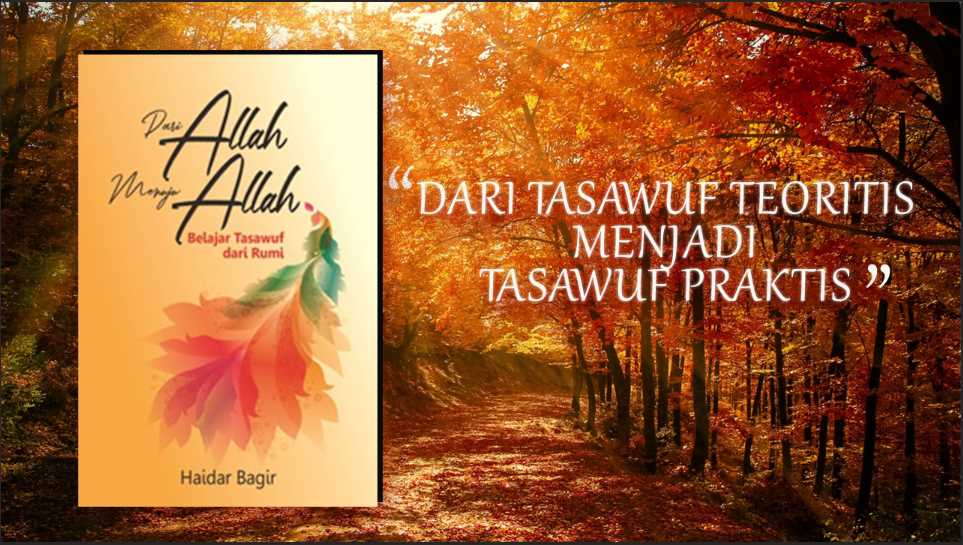Haidar Bagir
Dewan Pembina Nuralwala: Pusat Kajian Akhlak dan Tasawuf
Kalau dilihat dari bentuknya, puisi jelas merupakan bentuk yang lebih polos ketimbang prosa karena puisi lebih bersahaja dan apa adanya dalam mengungkapkan ilham kepenyairan, melalui kalimat lebih pendek-pendek yang efisien, dan lebih tak merasa perlu untuk melakukan penjelasan logis sebagaimana prosa. Meskipun demikian, ada juga prosa yang relatif lebih liar. Karya-karya Salman Rushdie adalah contoh yang baik mengenai bentuk ini.
Memang, bagi yang tidak percaya pada karya imajinatif yang terus terang dan apa adanya, atau yang percaya bahwa imajinasi cenderung menghasilkan penyelewengan pemikiran, bisa juga daya khayal disalurkan kepada karya-karya seni yang sober (“waras”, tidak “mabuk”). Dalam arti, sejalan dengan pakem-pakem rasional, mungkin juga filosofis dan religius, sebagaimana diajarkan oleh tradisi agama (kitab suci, sabda nabi, dan orang suci yang reliable, dan sebagainya).
Meski mungkin dipercayai bahwa nilai seninya bisa berkurang—bahkan juga boleh jadi kandungan keotentikannya tereduksi—hasilnya bisa lebih terkendali, lebih terpahamkan oleh orang banyak, dan kemungkinan penyelewengannya lebih kecil. Inilah sikap yang, saya kira, diambil oleh umumnya para seniman klasik, atau seniman religius, atau bahkan seniman modern tertentu yang memujikan sobriety.
Kisah-hidup Sutarji sebagai penyair—sesungguhnya juga beberapa penyair Indonesia lainnya—saya kira bisa menjadi ilustrasi yang menarik. Pernah ada masa ketika ia dikenal sebagai “penyair bir.” Inilah barangkali fase dalam hidupnya ketika dia mengandalkan pada daya khayal apa adanya. Dan memang, mood inducing drugs or substance tertentu—obat bius, LSD (dulu), anggur, termasuk bir—dipercayai bisa membantu orang untuk “naik” ke alam imajinal ini.
Sebagian filosof dan penyair masa lampau konon juga mengandalkan sebatas-terkendali penggunaan mood inducing substance ini, seperti Ibn Sina. Ibn Sina memang juga dikenal dengan karya-karya puitik serta prosa liris yang, oleh Henry Corbin, disebut sebagai resital-resital visioner. Mungkin juga penyair-penyair tertentu, seperti Omar Khayam yang didakwa bukan hanya sekadar menggunakan ungkapan-ungkapan “anggur” sebagai simbolisme, melainkan benar-benar minum anggur.
Hal ini barangkali juga terkait erat dengan pandangan sebagian filosof tersebut di atas yang mengaitkan pelepasan daya khayal dari berbagai pembatasan-pembatasan yang mengikatnya dalam keadaan rileks (flow state), seperti dalam tidur atau dalam keadaan-keadaan ekstrem tertentu seperti disebut sebelumnya.
Keadaan “naik” (fly, yang tak mesti sampai ke tingkat benar-benar mabuk) barangkali juga dipercayai sebagai termasuk salah satu di antaranya. (Perlu sambil lalu saya sampaikan di sini pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya, para pemikir dan penyair yang memang menggunakan sejenis mood inducing substances, memang berpendapat bahwa sejenis minuman tertentu seperti ini memang diperbolehkan oleh agama. Dalam tradisi awal Islam, diriwayatkan bahwa sebagian kaum Muslim biasa meminum setakar nabidz—kurma fermentasi, dicampur air—meski dalam jumlah banyak minuman ini bisa memabukkan. Wallahualam. Mazhab Hanafi, yang banyak dianut antara lain di Turki, kabarnya termasuk yang menoleransinya.)
Belakangan, kembali pada Sutarji, tampaknya dia lebih memilih untuk “mengendalikan” ilham-ilhamnya dengan perasaan religius, kalau malah bukan dengan daya rasionalnya. Atau, barangkali, ia hanya merasa bahwa ilham tak mesti dipancingnya dengan kemabukan akibat bir, yang diketahui banyak mudaratnya. Yang pasti, belakangan Sutarji meninggalkan ritual minum untuk kegiatan-kegiatan puitiknya.
(Nuralwala/DA)