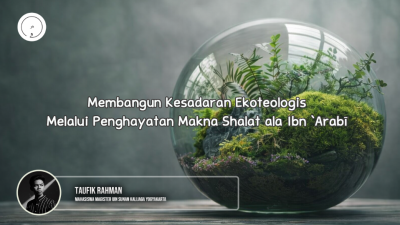Di zaman ini, mengatakan bahwa “setiap orang punya kelemahan dan kekurangan” terdengar sopan, tetapi semakin tidak memadai. Kalimat itu terlalu ringan untuk menggambarkan kondisi manusia hari ini. Ia tak lagi mampu menangkap skala kompleksitas batin dan relasi yang kita hidupi bersama. Mungkin kita perlu mengatakan sesuatu yang lebih jujur, meski tidak nyaman: hari ini, semua orang adalah orang dengan special needs.
Namun, bahkan sebelum sampai ke sana, ada satu kesadaran dasar yang sering kita abaikan: setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Tidak sama dengan kita, dan tidak sama satu sama lain. Cara orang berpikir, merasakan, merespons, dan menafsirkan dunia dibentuk oleh banyak hal—keluarga, budaya, pengalaman hidup, luka lama, dan juga keterbatasan psikologis yang sering kali tidak kasatmata.
Masalahnya, perbedaan ini jarang hadir dalam bentuk ekstrem. Justru yang paling sering merusak relasi adalah kekurangan-kekurangan kecil—hal-hal sepele yang, jika tidak dipahami, perlahan berubah menjadi sumber frustrasi besar.
Misalnya, seseorang yang mengalami time blindness—kesulitan mengelola waktu dan memperkirakan durasi, sesuatu yang lazim pada orang dengan ADHD. Bagi pasangannya, ini mudah dibaca sebagai ceroboh, tidak peduli, atau tidak menghargai. Padahal sering kali ini bukan soal niat, melainkan keterbatasan fungsi pelaksanaan (eksekusi) aktivitas sehari-hari.
Atau orang yang cuma tidak bisa multitasking. Ia hanya mampu fokus pada satu hal dalam satu waktu, sehingga tampak lambat, tidak sigap, atau “tidak peka”. Padahal sistem kerjanya memang demikian. Ada pula orang yang kadang absent-minded—pikirannya mudah melayang—bukan karena tidak peduli, tetapi karena cara otaknya memproses informasi.
Belum lagi mereka yang spontan mengomentari hampir semua hal: kejadian kecil, keputusan pasangan, atau hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikomentari. Ini sering disalahpahami sebagai sikap mendikte, ikut campur, atau menggurui, padahal bagi sebagian orang itu hanyalah cara alami untuk terhubung dan berpartisipasi dalam percakapan. Ada juga yang memiliki kecenderungan OCD ringan—rapi berlebihan, perfeksionis, sehingga terdengar menjengkelkan (nagging). Ini bisa terasa melelahkan dan mengontrol, padahal bagi yang bersangkutan, ketertiban adalah cara bertahan dari kecemasan.
Semua ini diperparah oleh perbedaan gaya komunikasi, yang sangat sering terjadi tetapi jarang disadari. Ada orang yang terbiasa berbicara lugas dan langsung karena budaya keluarganya demikian; ada yang terbiasa berputar-putar demi menjaga perasaan. Ada yang merasa kejujuran berarti bicara apa adanya; ada yang merasa kejujuran harus dibungkus dengan kehangatan. Ketika dua gaya ini bertemu, konflik sering muncul bukan karena isi pesan, melainkan karena cara pesan itu disampaikan.
Dalam konteks hubungan suami–istri, kekurangan-kekurangan kecil ini menjadi sangat menentukan. Pernikahan adalah relasi intens dengan frekuensi interaksi tinggi. Hal-hal yang di awal tampak sepele, lama-lama terakumulasi menjadi rasa jengkel, kecewa, bahkan marah. Yang satu merasa tidak dipahami; yang lain merasa selalu disalahkan. Padahal sering kali masalahnya bukan pada niat buruk, melainkan pada ketidakmampuan memahami perbedaan cara kerja batin pasangan.
Di sinilah kesadaran bahwa semua orang adalah special needs menjadi penting. Bukan untuk memberi label, apalagi menghindari tanggung jawab, tetapi untuk mengganti cara kita menafsirkan perilaku orang lain. Dari “dia sengaja begitu” menjadi “mungkin memang begini cara dia bekerja”. Dari reaksi emosional menjadi respons yang lebih tepat.
Tentu, memahami tidak berarti membenarkan segalanya. Ada perilaku yang tetap perlu dibatasi, dikoreksi, bahkan dihentikan. Namun tanpa pemahaman, koreksi sering salah sasaran—terlalu keras pada hal yang sebenarnya bukan pilihan, atau terlalu lunak pada hal yang justru berbahaya. Prinsipnya selalu adalah connect before correct. Memaklumi tidak sama dengan membenarkan, tetapi tanpa memaklumi, upaya memperbaiki kemungkinan besar akan gagal.
Kesadaran ini juga melindungi kita dari kekecewaan kronis. Banyak konflik rumah tangga berakar pada ekspektasi yang tidak realistis: berharap pasangan selalu peka, selalu tepat waktu, selalu mengerti maksud kita, selalu berkomunikasi dengan gaya yang kita anggap benar. Padahal pasangan kita, seperti kita sendiri, memiliki keterbatasan.
Dan pada akhirnya, kita perlu mengingat satu hal yang paling sulit sekaligus paling jujur: kita pun orang dengan special needs. Kita pun punya sisi-sisi kepribadian yang menyulitkan orang lain—entah itu keras kepala, defensif, sensitif berlebihan, atau sulit berempati. Jika kita ingin dipahami, dimaafkan, dan dibantu menjadi lebih baik, maka orang lain pun—termasuk pasangan hidup kita—menginginkan hal yang sama.
Mungkin, di zaman yang semakin kompleks dan menekan ini, kedewasaan bukan lagi soal menjadi pribadi tanpa cela. Kedewasaan justru terletak pada kemampuan untuk hidup bersama perbedaan keterbatasan, tanpa saling melukai, tanpa menormalisasi yang destruktif, dan tanpa kehilangan kemanusiaan.
Jika tidak, relasi kita bukan hanya akan penuh konflik, tetapi juga penuh kekecewaan—karena kita terus berharap orang lain menjadi versi ideal yang sebenarnya tidak pernah ada.