Ada saat dalam hidup ketika kita tiba-tiba seperti jatuh murung nyaris tanpa sebab, lalu terungkap tanya: Sebetulnya, aku ini mau jadi apa? Pertanyaan sederhana ini ternyata sangat dalam. Di baliknya ada rasa takut, cemas, bingung, dan sepi. Para filsuf eksistensialis Barat melihat momen seperti ini sebagai momen paling menentukan dalam hidup manusia.
Soren Kierkegaard, misalnya, mengatakan bahwa manusia baru sungguh menjadi “diri”-nya ketika ia berani menghadapi kecemasan dan ketidakpastian hidupnya sendiri. Bagi Kierkegaard, kecemasan bukan musuh—ia adalah tanda bahwa jiwa sedang menuju kedewasaan.
Martin Heidegger menambahkan bahwa manusia sering hidup dalam rutinitas sosial tanpa ujung pangkal—mengikuti arus, ekspektasi, dan standar orang lain—sampai akhirnya ia dihentikan mendadak oleh satu pertanyaan batin yang memukul-mukul. Saat itu, kata Heidegger, manusia mulai merasakan keautentikan: keberadaan yang sungguh milik dirinya. Ketika semua relasi dengan yang di luar seperti terputus. Sehingga, pada saat yang sama, ia harus mengidap Angst (anxiety, kecemasan).
Jean-Paul Sartre melihat lebih jauh: bagi dia, manusia itu “dikutuk untuk bebas.” Kita harus memilih jalan kita sendiri. Tidak ada yang bisa memilihkan bagi kita. Dan itulah yang membuat kita gamang dan takut dalam kebebasan itu.
Albert Camus berbicara nyaris sama, hanya dengan nada lain: Hidup ini dapat terasa absurd—penuh pertanyaan tanpa jawaban pasti. Tetapi justru dalam absurditas itu manusia menemukan martabatnya: ketika ia tetap memilih untuk hidup, untuk berjalan, untuk mencari makna.
Semua pemikir ini sepakat dalam satu hal: pertanyaan batin yang muncul dari kesepian dan kecemasan adalah awal kelahiran diri. Dan inilah yang tergambar dalam lagu Yura Yunita terbaru berjudul. “Mau Jadi Apa?” Pertanyaan eksistensialis sebuah hati yang mulai menyadari dirinya.
Dalam tradisi para sufi, pencarian seperti ini hampir selalu dimulai dengan tekanan kesedihan batin. Kesedihan yang lebih sering tidak jelas penyebabnya. Kesedihan yang membuat kita tidak bisa lain kecuali mencari jawab atas pertanyaan batin itu. Bahkan ini adalah pertanyaan profetik, yang mengawali pertemuan para Nabi dengan Tuhan. Ibrahim menemukan Tuhan dalam kesendirian panjang. Musa bertemu Tuhan dalam kebingungan. Yesus menyeru Tuhan dalam kesepian. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama setelah periode kegalauan-meditatif. Sungguh kesedihan adalah rahim kelahiran spiritual.
Para sufi lebih jauh menekankan bahwa kesedihan dan kerinduan kita sebenarnya adalah gema dari cinta Tuhan sendiri. Tuhan bukan jauh, dingin, kaku. Ia al-Wajid—Pencipta yang Pencinta. Ia ar-Raḥmān—Sang Welas asih. Ia Tuhan yang dekat, yang peduli, yang menunggu.
Dalam sebuah hadis Qudsi yang sering dikutip para sufi, bahkan yang menjadi kunci seluruh kosmologi sufi: “Aku adalah Perbendaharaan Tersembunyi. Aku cinta-rindu untuk dikenali, maka Kuciptakan makhluk agar Aku dikenali.”
Dengan kata lain: kita mencari Tuhan karena Tuhan yang merindu untuk ditemukan sedang menarik kita kepada-Nya. Sebagian menerjemahkannya dengan menyebut Tuhan sebagai “the Pathetic God”. Bukan dalam arti Tuhan yang lemah, melainkan Yang Penuh Rasa, Penuh Simpati, Penuh Cinta. Dan di titik ini, kalimat “mau jadi apa?” dalam lagu Yura Yunita mendapatkan maknanya.
Sudah pasti lagu ini bukan hanya soal kesuksesan dalam pekerjaan, atau dalam meraih popularitas—meski ilustrasi video clipnya secara manis sekaligus agak parodik dan surealistik, berkisah tentang kesibukan dan mimpi-mimpi sekelompok atau sekeluarga (seperti) penari ludruk. Lagu ini adalah perenungan tentang batin terdalam keruhaniahan kita. Tentang sesuatu yang lebih besar dari diri kita.
Konon, lagu “Mau Jadi Apa?”, yang ilhamnya diperoleh Yura saat mendaki gunung, ini memang mengisahkan pertanyaan tentang hakikat jati diri manusia. Suatu pertanyaan eksistensial yang di zaman ini menjadi lebih membebani jiwa oleh tekanan dan ekspektasi sosial, terutama di kalangan generasi muda.
Alhasil, jika menurut para filsuf eksistensialis pertanyaan itu adalah awal kesadaran diri maka, menurut kaum sufi pertanyaan itu adalah panggilan Tuhan dari dalam hati kita. Karena, pada akhirnya, orang yang sungguh-sungguh mencari dirinya, sedang menjelang pertemuan dengan Tuhannya. Dan orang yang mencari Tuhan, akan menemukan dirinya.
Kesedihan eksistensial adalah tanda awal perjalanan. Pertanyaan adalah tanda bangkitnya jiwa. Dan lagu ini mungkin sedang mengajak kita untuk kembali pulang—kepada diri kita sendiri, dan kepada Dia yang telah menanamkan makna itu di dalam hati kita sejak awal.








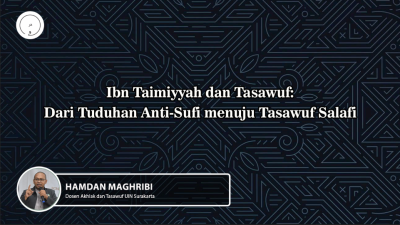
🤍